Sembari menulis pengantar ini, dunia kita sedang menghadapi berbagai tantangan. Pertama, kita berada di tenga pandemi yang memporak-porandakan kehidupan normal kita. Kedua, rasisme sistemik yang telah mengakar kuat dan terus memakan korban jiwa serta menghalalkan perilaku diskriminatif terhadap saudara-saudari kita yang berbeda etnis. Keduanya, pandemi dan rasisme sistemik, saling berkaitan. Keduanya menunjukkan kepada kita bahwa ketimpangan, baik ekonomi maupun rasial, terus menyebabkan luka dan penderitaan.
Tantangan ini membuat kita menyadari bahwa kerajaan damai Tuhan belum menjadi realita di bumi. Namun bila kita memerhatikan jeritan mereka yang tidak bisa bernapas – baik karena COVID-19 atau karena kebrutalan aparat – kita bisa belajar bersolidaritas dengan mereka yang sakit dan tertindas.
Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan berjalan bersama mereka yang putus asa, tertindas dan menderita. Alkitab juga mengundang mereka yang percaya pada Yesus Kristus untuk melihat bahwa: semua manusia memiliki interkonektivitas (saling ketergantungan). Ketika ada yang tidak sehat atau menderita, ciptaanNya tidak sesuai rancanganNya. Bila kita ingin merefleksikan damai dan keadilan Tuhan di bumi ini, apa yang terjadi pada satu bagian berdampak pada, dan perlu diperhatikan oleh, bagian lainnya. Bila kita ingin menjadi gereja yang membawa damai, kita harus menyadari interkonektivitas kita, menentang ketidak adilan, dan mendampingi mereka yang menderita.
Menyadari interkonektivitas kita berarti mempertanyakan konsep “individu”, yang mengajarkan bahwa satu orang “bebas” atau “terpisah” dari yang lain. Konsep ini berasumsi bahwa satu orang bisa “independen” dari lainnya. Karenanya, perang yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita ingin menekankan “individu” adalah keinginan untuk bebas dari orang-orang lain.
Satu hal yang ditunjukkan oleh COVID-19 dalam beberapa bulan ini adalah bahwa kita semua terikat satu dengan yang lain. Abainya satu orang bisa berakibat buruk bagi satu komunitas. Demikian pula kewaspadaan banyak orang bisa memberi perlindungan bagi satu dua orang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sederhananya, apa yang saya lakukan berdampak pada orang lain, dan apa yang orang lain lakukan berdampak pada saya. Penyebaran COVID-19 membuat kita sadar akan adanya interkonektivitas.
Di Afrika Selatan, ada satu peribahasa umuntu ngumuntu ngabantu yang berarti “orang jadi orang karena orang lain.” Singkatnya, peribahasa ini dikenal sebagai ubuntu.
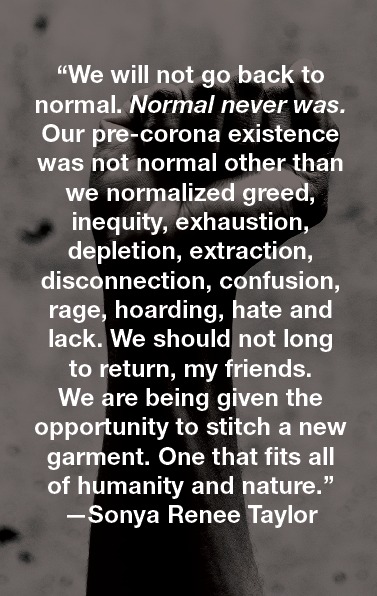
Di Afrika Selatan, ubuntu memberikan logika alternatif terhadap sejarah penjajahan dan apartheid. Apartheid, yang secara literal berarti “pemisahan” atau “apart-hood”, adalah sistem pemisahan berdasarkan ras yang bersumber pada penjajahan Eropa yang membentuk sistem hukum yang didasarkan pada keunggulan kulit putih dan menindas mereka yang dianggap “non kulit putih”. Apartheid adalah rekayasa sosial yang mempromosikan pemisahan dan ketakutan akan kelompok yang “lain”, sehingga menghalalkan penindasan dan kekerasan terhadap mereka yang bukan kulit putih.
Sepanjang perjuangan melawan apartheid yang akhirnya dihapuskan di tahun 1994, konsep ubuntu memberikan arahan. Ubuntu menunjukkan bagaimana apartheid dan politik pemisahan menghancurkan tidak hanya harga diri seseorang, tapi juga rasa kemanusiaannya! Desmond Tutu, misalnya, berkali-kali menyebut ubuntu ketika menentang logika dan praktik pemisahan dalam apartheid. “Rasa kemanusiaanku,” dia menyebutkan, “terikat dan tak terpisahkan dengan rasa kemanusiaanmu. Demikian pula sebaliknya.” [1]
Namun mengadopsi konsep interkonektivitas seperti ini ada konsekuensinya. Apa yang terjadi pada saudara kita berdampak pada kita, dan apa yang terjadi pada kita berdampak pada orang lain. Hal-hal yang terjadi berdampak tidak hanya pada gambar diri kita, tapi bagaimana kita bertindak! Dengan kata lain, konsep ini mengedepankan visi sosial, bukan visi individu!
Karenanya, bila kita ingin sehat, kita juga harus berupaya untuk memastikan bahwa orang di sekitar kita sehat. Bila kita menginginkan dunia dimana tiap orang mendapat perlakuan dan respek yang sama – sebagai gambar dan karunia Allah – kita harus memastikan bahwa mereka yang termarjinalkan di mata penguasa mendapat perhatian khusus dalam perjuangan kemanusiaan kita. Di level paling fundamental, inilah artinya hidup dalam solidaritas dengan orang lain.
Untuk hidup dalam solidaritas berarti kita perlu mengerti tantangan yang orang lain sedang hadapi. Dengan kata lain, bersolidaritas berarti kita perlu menyadari dan mempertanyakan kembali realita sosial apa yang selama ini kita percayai, supaya kita bisa belajar lagi mengapa, dan bagaimana, orang lain mengalami penderitaan.
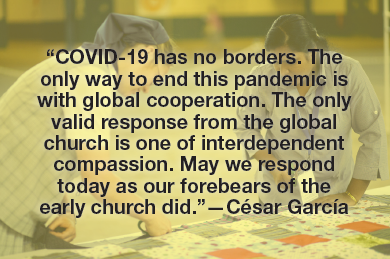
Di sini pentingnya “ratapan”. Untuk mengerti ratapan – tangisan dan kepiluan seseorang – kita perlu mengakui bahwa ada hal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ratapan memotivasi kita untuk menyelidiki mengapa penderitaan itu terjadi dan bagaimana menghadapi penyebab penderitaan tersebut. Ratapan memberikan kesempatan untuk belajar mengenai apa yang tidak berfungsi, bahwa harmoni belum tercapai, dan apa yang perlu diperbaiki agar semua orang bisa merasakan damai sejahtera Tuhan.
Renungan ini mengundang gereja menjadi “persekutuan orang-orang terpanggil”. Renungan ini mengajak kita menjadi gereja yang bersolidaritas dengan sesamanya; terutama mereka yang sulit untuk mendapatkan akses kesehatan, gizi, kesempatan ekonomi, jaminan sosial dan perlakuan yang bermartabat.
Ketika kita merespon panggilan untuk menjadi gereja Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan beserta kita, bekerja melalui kita, dan tidak akan meninggalkan kita. Panggilan ini memberi tantangan agar dalam pekerjaan kita di dunia, kita membawa damai Tuhan dan menjadi saksi damai Kristus.
Semoga Tuhan membantu kita untuk menjawab panggilanNya dengan setia.
—Andrew Suderman
Este testimonio hace parte de los recursos para la adoración del Domingo de la Paz 2020. Haga clic aquí para ver más.
[1] Desmond Tutu, No hay futuro sin perdón, 1ra ed. (New York: Doubleday, 1999), 31.